NAVIS DAN/SEBAGAI TEKS/WACANA:
KEMARAU YANG MENGG/HALANG
ROBOHNYA SURAU KAMI
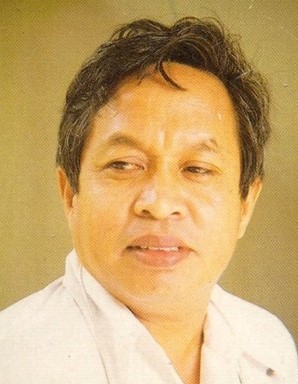 JUDUL ini mesti dibaca beberapa kali. Bagian pertama empat kali: Navis dan teks, Navis sebagai teks, Navis dan wacana1 dan Navis sebagai wacana. Bagian kedua empat kali: Kemarau yang menggalang robohnya surau kami, Kemarau yang menghalang robohnya surau kami, Kemarau yang menggalang ‘Robohnya Surau Kami’ dan Kemarau yang menghalang ‘Robohnya Surau Kami’. Alasan pembacaan demikian anda ketahui nanti. Di sini saya hanya akan bicara tentang hal yang perlu dieksplisitkan.
JUDUL ini mesti dibaca beberapa kali. Bagian pertama empat kali: Navis dan teks, Navis sebagai teks, Navis dan wacana1 dan Navis sebagai wacana. Bagian kedua empat kali: Kemarau yang menggalang robohnya surau kami, Kemarau yang menghalang robohnya surau kami, Kemarau yang menggalang ‘Robohnya Surau Kami’ dan Kemarau yang menghalang ‘Robohnya Surau Kami’. Alasan pembacaan demikian anda ketahui nanti. Di sini saya hanya akan bicara tentang hal yang perlu dieksplisitkan.
‘Navis dan teks dan wacana’ mengemukakan hakikat teks dan wacana Navis yang adalah ‘reaksi’ terhadap berbagai teks dan wacana lain, dan dapat dipahami dengan membacanya secara intertekstual dengan teks dan wacana lain yang kita, atau saya, anggap bertanggung jawab untuk kehadirannya.
Dengan ‘Navis sebagai teks dan wacana’, karangan Navis saya lihat bukan sebagai cerita. Kita mesti memperhitungkan unsur teks dan wacana yang biasa diabaikan orang bila bicara tentang cerita. Cerita, sama dengan buku, dan bertentangan dengan pengertian Derrida tentang hakikat teks dan wacana yang terbuka (G. Douglas Atkins, 1983:39), adalah tertutup2. Orang dapat menutup cerita tapi tak mungkin menutup wacana dan teks. Sebagai cerita, ‘Datangnya dan Perginya’, ‘Pada Pembotakan Terakhir’ dan ‘Menanti Kelahiran’ sama saja pada dua edisi Robohnya Surau Kami (1966, Nusantara dan 1990, Gramedia). Tapi masing-masingnya, sebagai wacana dan teks berbeda-tak akan dibicarakan di sini karena perlu pembicaraan tersendiri.3 Hakikat perbedaan teks dan wacana pada suatu pihak dan cerita pada pihak Iain pada pembicaraan ini akan dilihat dalam hubungan perbandingan antara Kemarau (1967)—diseIesaikan Navis di Maninjau 8 Maret 1964—dan ‘Datangnya dan Perginya’—dikarang Navis di Bukittinggi 18 Januari 1956—yang selanjutnya dapat dihubungkan dengan ‘Robohnya Surau Kami’, dikarang Navis di Bukittinggi Maret 1965. Dan ini membawa saya kepada bagian kedua judul tadi.
—————————–
1Pengertian wacana pada saya bukan pengertian liguistik, tapi pengertian ilmu sosial dan filsafat, yang terutama dihubungkan dengan pemikiran Michael Foucault (Diane Macdonell, 1986: Norman Fairclough, 1993) hingga mungkin saja ada wacana sosial, politik dan sebagainya. Dalam bereaksi kepada berbagai wacana ini, Navis membentuk wacana sendiri, yang lebih dari hanya wacana sastra yang membatasi diri kepada cerita. Dan ini yang akan saya olah dalam pembicaraan ini.
2Dalam ‘Navis dalam dua muka’ (1972) Kemarau dan ‘Datangnya danPerginya’ saya lihat sebagai satu cerita dengan dua akhir yang berbeda. Ini berbeda dengan sikap saya pada pembicaraan ini. Keduanya adalah wacana dan teks. Akibat adanya perhatian terhadap unsur yang sebelumnya luput dari perhatian. Anda tidak perlu heran bila kesimpulan saya pada pembicaraan ini lain dari sebelumnya. Dan ini biasa. Perbedaan kesimpulan kita tentang sesuatu, sesuai dengan pandangan Niels Bohr, penggagas teori quantum, tentang fisika (Paul Davies & John Gribbin, 1991:21) bukan karena kelainan materi, tapi karena kelainan cara melihat sesuatu. Pembicaraan kini tentu akan menolak anggapan Gabriel Josipivici (1973:296) bahwa seorang pengarang hanya mengarang satu novel. Secara cerita, seorang pengarang mungkin hanya menulis satu novel. Kemarau dan ‘Datangnya dan Perginya’ secara cerita satu, hanya akhirnya saja yang berbeda. Tapi tak demikian halnya secara teks. Keduanya adalah dua teks yang berbeda. Ini makin kentara bila kita mula memperhitungkan perbedaan teks antara dua cerita yang sama, misalnya perbedaan teks antara cerpen Navis dalam Robohnya Surau Kami edisi 1965 dan 1990.
3Dalam membicarakan hal ini, perhatian kita bukan hanya tentang perbedaan materi kedua ‘buku’ itu, juga persoalan mengapa terjadi perbedaan materi itu, persoalan yang diolah pada kritik genetik (Junus, 1989:149—159). Kita pertanyakan siapa yang bertanggung jawab melakukannya, pengarang, penerbit atau tangan lain, dan mengapa dilakukan. Apakah perbedaan itu hanya perbedaan materi bahasa atau lebih dari itu. Perlu diingat, edisi 1990, lain dari sebelumnya, adalah edisi sekolah. Bukan tak mungkin ini berpengaruh terhadap perubahan itu. Dan ini menghendaki pembicaraan tersendiri.
Kemarau menggalang ‘Robohnya Surau Kami’ yang sebagai pernah saya bicarakan di Kompas—saya lupa tanggalnya—adalah cerpen yang silepsis.4 Dalam percaya ia menolak pandangan kolot garin, malah membenci garin kolot itu, kita juga percaya ia juga menyayangkan kematian garin itu, kematian yang menyebabkan ‘surau kami’ roboh dan hilangnya syiar agama. Dan Kemarau, saya rasa, telah mengisi kekosongan itu dengan unsur yang dalam ‘Datangnya dan Perginya’ masih dalam bentuk embrio. Duano memang seorang garin namun Iain dari garin ‘Robohnya Surau Kami’. Kemarau menghalang robohnya surau kami. Kedatangan Duano ke kampung di tepi danau itu, mendiami surau tinggal, yang menurut ‘Robohnya Surau Kami’ hanya menunggu roboh, berjaya menghidupkan kembali kehidupan surau yang suasanya lain dari kehidupan mesjid—ini membawa saya kepada novel Tamu (1994) Wisran Hadi yang diserialkan dalam Republika.5 Kemarau berjaya menghalang ‘Robohnya Surau Kami’ dan robohnya surau kami. Memberikan alternatif lain terhadap ‘Robohnya Surau Kami’, yang berhubungan dengan pengertian tentang agama yang akan diberikan nanti.
—————————
4Ini istilah Michael Riffaterre (1980). Biasanya disamakan dengan ambiguos. la saya pilih atas alasan teknikal. la berhubungan dengan suatu keadaan di mana ada berbagai makna, kita tidak dapat meniadakan kehadiran makna lain. Kita hidup dalam suasana dialog antara berbagai makna.
5Ongga dalam Tamu keberatan suraunya dimesjidkan oleh ‘tamu’ karena ini menyebabkan surau berhenti jadi milik keluarga besarnya. Surau bagi Wisran adalah bagian dari sistem adat dan keluarga Minang: tempat keluarga bersidang, persinggahan remaja dan orang dewasa yang tak punya isteri. Ini tak ada pada mesjid yang tugas utamanya menyangkut ‘upacara’ formal agama. Meskipun Navis seakan membedakan fungsi mesjid dan surau, namun ia tak menghubungkan surau dengan adat dan keluarga Minang. Sesuai dengan keinformalan surau berbanding mesjid, surau dalam Kemarau dianggapnya (dapat) memberikan alternatif terhadap suasana keagamaan mesjid yang formal. Melalui surau, Duano yang pendatang menyebarkan pemahaman baru terhadap kehidupan beragama, dengan harapan ia akan dapat mengubah pemikiran yang selama ini telah menguasai penduduk kampung itu. Ini lain dari ‘Datangnya dan Perginya’. Orang bukan menghuni surau, tapi menghuni mesjid yang sebagai dikatakan tadi punya fungsi yang berbeda. Tapi perlu diingat ini hanya pernyataan awal yang memerlukan penelitian dan pemikiran lebih lanjut.
Sama dengan tanggapan kita tentang hubungan antara cerpen Armijn Pane sebelum perang, diterbitkan 1953, dan Belenggu (1940)—ada yang dianggap Armijn hanya latihan—yang dapat dibandingkan dengan pendapat Budi Darma (1984:21), ‘Robohnya Surau Kami’ mungkin digunakan Navis sebagai latihan mengarang Kemarau. Apalagi memang ada pemikiran Kemarau yang dapat dianggap perluasan pemikiran yang dalam cerpen masih berbentuk embrio.6 Namun kita juga dapat mempertanyakan kesimpulan ini karena penutup cerita keduanya berbeda. Dan ini tidak terjadi begitu saja. Duano dalam Kemarau Iain dari orangtua pada ‘Datangnya dan Perginya’. la kelihatan dipersiapkan untuk akhir yang berbeda dan ini memaksa Navis mengakhiri Kemarau lain dari cerpennya. Keduanya adalah dua wacana dan teks yang berbeda. Dan karena tidak mungkin membicarakan setiap perbedaan kedua teks itu, terpaksa ada yang diabaikan. Dan sesuai dengan hakikat keterbukaan teks, saya sadar unsur yang diabaikan itu dapat membawa orang lain ke arah Iain, namun saya tak dapat berbuat lain. Ini adalah konsekuensi yang mesti dihadapi dalam dunia ilmu. Selalu ada yang mesti diabaikan.
————————–
6Datangnya dan Perginya’ hanya mengatakan orangtua itu, yang kini sudah insaf akan kesalahannya, telah berhijrah ke dusun yang jauh dan tinggal di mesjid, mengabdikan diri kepada Tuhan. Karena itu, surat Masri yang diterimanya diselipkannya di antara lembaran Qur’an. Ini lain dari Kemarau. Duano memang berhijrah juga ke desa. Namun bukan dia di mesjid, tapi di surau, yang dalam tradisi Islam Minang punya fungsi lain selain fungsi formal yang ada pada mesjid. Antara lain ia berfungsi sebagai pusat pendidikan agama. Seorang menyebarkan ajaran agama dari surau, bukan dari mesjid. Dalam ‘Datangnya dan Perginya’, Qur’an milik orangtua mungkin sembarang Qur’an: yang hanya perlu dilagukan tanpa perlu dipahami. Tidak demikian hanya dengan Duano dalam Kemarau. Rujukan ialah Qur’an tafsir Sudewo yang pembacaannya membawa orang kepada pemahaman. Orang tidak lagi terikat kepada keindahan pembacaannya dalam bahasa Arab tanpa ada kewajiban untuk memahaminya. Orang tak lagi terperangkap dengan anggapan tentang kesaktian Qur’an sebagai wacana yang berasal dari Tuhan hingga ada orang yang menggunakannya seakan mantra, menyembuhkan penyakit. Dan dalam sejarah Islam di Indonesia, tafsir Sudewo biasa dihubungkan dengan pemikiran modern Islam. Dan karena ditulis dalam bahasa Belanda, ia membatasi khalayaknya kepada intelektual Indonesia—biasanya sinonim dengan orang yang berpendidikan Belanda. Ini ditambah dengan hakikat Duano yang belajar agama dari buku-buku—wacana intelektual—bukan dari guru agama tradisional. Jadi ada transformasi pemikiran dari ‘Datangnya dan Perginya’ kepada Kemarau yang nanti juga akan dibicarakan.
Cerpen ‘Datangnya dan Perginya’ membawa kita menumpukan perhatian pertemuan hubungan orangtua dan anaknya. Keresahan orangtua menunggu pertemuan dengan anaknya membawa kita berkenalan dengan sebab mereka berpisah: kegagalan orangtua menemukan isteri pertamanya pada setiap isteri yang dikawininya setelah kematian isteri pertamanya. Dan bila kita membaca Kemarau setelah membaca cerpen itu, kita juga akan berusaha menemukan unsur itu karena ia juga kita anggap menguasai Kemarau. Atau dalam membandingkan dengan cerpen itu kita cenderung untuk menumpukan perhatian terhadap unsur lain, yang menyamakan dan sekaligus memisahkan keduanya. Ini tidak salah. Dalam bekerja dengan sesuatu kita selalu dan memang dikuasai oleh konsep yang pernah kita miliki tentangnya.7 Namun, perlu dijaga agar ia tak menyebabkan kita lupa akan kehadiran unsur lain yang bagian dari wacana Kemarau.
————————–
7Ini sesuai dengan pemikiran Borh. Perbedaan pandangan terhadap sesuatu bukan karena perbedaan materinya, tapi karena perbedaan cara melihatnya. Dukun urut mencari sebab penyakit pada kesalahan urat. Sedang dukun yang seorang shaman mencari sebabnya pada kehadiran unsur jahat dalam diri si sakit, mungkin perbuatan orang. Dan seorang yang kuat keyakinan agamanya mungkin menghubungkannya dengan dosa. Seorang sakit karena hukuman Tuhan terhadap dosanya. Dan seorang doktor akan mencari sebab lain: kesalahan urat, kelemahan organ karena tua, atau karena kehadiran virus dan bakteri dalam badan si sakit. Hal yang sama juga kita lakukan dalam kita membaca dan menganalisa suatu karya sastra. Kita mencari apa yang ingin kita temui, yang sebelumnya telah menguasai diri kita. Dalam hubungan ini perhatikan juga pengantar Edward W. Said yang mengantar Culture and Imperialism (1994:xixxxii). Dan kita hanya dapat membebaskan diri dari ikatan ini dengan memulakan pembacaan dengan wacana dan teks. Tapi ini saja tak cukup. Perlu ada syarat lain. Kita perlu membebaskan diri dari keterikatan kepada teori karena ini akan mengungkung perspektif pencarian kita, kita perlu mempersiapkan diri dengan berbagai teori yang bukan hanya memperluas perspektif kita, juga memungkinkan kita menemui hal yang selama ini luput dari perhatian.
Yang pasti, unsur yang mengesankan kita dalam membaca cerpen tadi dapat dibaca dalam hubungan wacana yang pernah ada, memuja cinta. Cinta dianggap segalanya dan seorang, seumur hidupnya, hanya satu kali jatuh cinta, dan ini adalah ‘semangat zaman’ (Junus, 1987), yang memang dapat disimpulkan sehabis membaca novel-vovel Balai Pustaka8. Rasa cinta kepada isteri pertama menyebabkan Duano dan orangtua mencari replika isteri pertama pada setiap isteri yang dikawininya setelah isteri pertamanya mati. Hanya dengan cara ini ia merasa bebas dari mengkhianati rasa cintanya kepada isteri pertamanya, cintanya yang pertama dan satu-satunya. Dan ini berakibat fatal. Tanpa sadar ia telah menceraikan seorang isteri yang lagi mengandung yang kemudian melahirkan Ami. Persoalannya jadi lebih runyam bila Arni kawin dengan Masri, anaknya yang dulu melarikan diri darinya. Mereka tak tahu mereka seayah. Dan Iyah, ibu Arni, yang terlambat tahu, takut memberitahu mereka. la takut menambah dosanya kepada anaknya yang hidup bahagia dengan suami dan anak-anaknya. la bersedia menanggung dosa itu. Anaknya bebas dari (rasa) dosa karena tak tahu hakikat hubungan mereka. Mereka tak tahu mereka berdosa.
————————-
8Tak ada pernyataan eksplisit tentang hal ini dalam novel-novel BP. Tapi ada hal yang menyebabkan orang sampai kepada kesimpulan ini. Ada anggapan hanya orang yang tak mengenal dunia cinta yang melakukan poligami. la menggunakan kuasanya, juga uang, untuk memuaskan seksnya. Dan untuk melaksanakan dunia cinta, orang mesti berusaha keluar dari dunia ini. Karena itu ada anggapan orang bersedia mati karena kegagalan cinta. Atau jadi gila. Dan sebagai wacana sosial ini pernah saya dengar masa kecil di kampung. Sesuai wacana ini remaja dilarang jatuh cinta. Salah satu caranya remaja dilarang membaca roman karena diduga memperkenalkan satu mereka dengan dunia cinta. Dalam tahun 1950-an, melalui wacana sastra, ini kita warisi sebagai wacana budaya sebelum perang. Setiap orang yang menganggap diri modern dan berpendidikan akan berusaha untuk tak beristeri banyak. Hanya kawin karena cinta. Sesuai dengan ini, sukar bagi seseorang menggantikan istrinya yang telah meninggal dengan seorang istri baru. la dianggap pengkhianatan kepada dunia cinta dan kejujuran cinta seorang kepada istri pertamanya. Dan ini yang saya anggap berlaku pada ‘Orangtua’ dan Duano. la tidak dapat bahagia dengan istri barunya, setelah kematian istri pertama. Dan karena keinginannya untuk mendapatkan perempuan lain hanya untuk kepuasan seks, ia akhirnya memuaskannya dengan pelacur, hubungan dagang yang bebas dari rasa cinta. Bebas dari pengkhianatan terhadap kesucian cinta. Namun ini tidak mutlak. la mesti berhadapan dengan nilai lain, yang menyebabkan ia bentrok dengan anaknya hingga anaknya memisahkan diri darinya yang juga ikut menentukan arah hidupnya selanjutnya. Dan ini tentunya juga berpengaruh terhadap perkembangan cerita, teks dan wacana.
Ada kelainan lain antara cerpen dan novel. Pada cerpen, meskipun ada perlawanan dari orangtua, namun ia rela menerima saran Iyah untuk meninggalkan rumah anaknya sebelum sempat bertemu anaknya. Menyerah kepada rasa kemanusiaannya yang melarangnya menceritakan hubungan persaudaraan Masri dan Arni. la bersedia menanggung dosa kepada Tuhan, membiarkan berlakunya suatu dosa, karena ia tak mau menambah dosa kepada manusia, terutama anaknya. Pembongkaran dosa itu akan menyengsarakan anak-anaknya yang kini hidup bahagia dan ini menambah dosanya kepada mereka apalagi bila mereka tidak bersedia memaafkannya, penyebab semuanya. Ini ditambah dengan dosa menghancurkan kehidupan suatu keluarga yang bahagia dan dosanya menyebabkan anak-anaknya merasa berdosa karena kawin bersaudara. Dalam cerpen itu diberikan rasional mengapa orangtua sampai mengambil keputusan demikian. Saya kutipkan dari edisi 1966:
Ketika ia sudah di seberang pintu dan sebelum pintu ditutupnya lagi, berkatalah ia dengan sayu: — Sebaiknya aku tak kemari, Iyah. Bahkan kalau dosa saja dalam hidup kita ini, sebaiknya juga kita manusia ini tak usah ada. Tapi manusia itu tetap juga ada dan Tuhan pun ada. Dosa kepada Tuhan, mudah mendapat ampunannya, karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tapi kalau dosa itu kepada manusia, sukarlah mendapat penyelesaiannya. Aku, aku tak hendak berbuat dosa lagi kepada manusia, apalagi jika manusia itu terdiri dari darah dagingku sendiri. Aku pergi Iyah. Dan jangan kau katakan pada siapa pun. Dan jangan kau cari aku. (83)
Dan ini saya lengkapi dengan kutipan dari edisi 1990 yang mungkin diabaikan orang karena dianggap bukan perubahan penting, namun sebagai teks dan wacana mengundang interpretasi yang menarik:
Dan sebelum pintu ditutupnya lagi, berkatalah ia dengan sayu: “Iyah, sebaiknya aku tak kemari. Bahkan kalau hendak memikul dosa-dosalah hidup kita ini, sebaiknya juga kita manusia ini tak usah ada. Tapi manusia tetap ada dan Tuhan pun ada. Dosa kepada Tuhan akan dapat ampunan-Nya kalau kita bertobat, Iyah, karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tapi dosa itu kepada manusia, sukarlah mendapat penyelesaiannya. Dan aku telah lama tidak berbuat dosa lagi kepada manusia,- apalagi terhadap manusia yang terdiri dari darah dagingku sendiri. Aku pergi Iyah. Dan jangan kau katakan pada siapa pun tentang kita, dan tentang apa yang kita lakukan ini. Kau tahu apa yang kita lakukan ini, Iyah?” (64)
Rasionalnya: Dosa kepada manusia tak berampun. Dan karena rahasia itu tidak diketahui orang Iain, ia hanya dosa mereka kepada Tuhan dan ini mudah mendapat ampun karena Tuhan pengasih dan penyayang—menyerahkan segalanya kepada Tuhan tanpa ada usaha manusia untuk memperbaiki dirinya. la menutup rahasia itu karena ia tak mau lagi berbuat dosa kepada manusia (edisi 1966), yang dalam edisi 1990, dikatakan tidak pernah lagi dibuatnya. Pada edisi 1966 ia—ketakmauan berbuat dosa kepada manusia—hanya suatu kemauan yang belum dikerjakan—sedang pada edisi 1990 itu adalah kehidupannya—ia tidak pernah lagi berbuat dosa kepada manusia9. Dari membaca penutup cerpen itu pada kedua edisi itu dapat dikesan adanya rasa penyerahan diri kepada pengampunan Tuhan. Mereka berani berdosa kepada Tuhan karena percaya Tuhan akan mengampunkan mereka. Dan takut berdosa kepada anak mereka karena takut tak akan mendapatkan maaf mereka di samping akan menyengsarakan hidup mereka. Ini berbeda dari sikap Duano dalam Kemarau yang peristiwanya adalah suatu fait accompli.
Berbeda dari orangtua, Duano tidak mengalah kepada Iyah. la tetap ingin memberitahu Masri dan Arni bahwa mereka seayah yang menurut agama dilarang kawin. Untuk mendiamkan Duano, Iyah yang tidak punya pilihan Iain terpaksa memukulnya. Tapi ia gagal melanjutkan pukulannya karena keburu ditegah Masri yang pulang bersama Arni dan anak-anaknya. Sadar akan kesalahannya setelah melihat keadaan Duano yang parah, Iyah memberitahu Arni dan Masri bahwa Duano adalah ayah mereka. Iyah yang jatuh pingsan setelah membuka rahasia yang selama ini ditutupinya selanjutnya dilupakan.
—————————-
9Ini dapat dianggap sebagai petunjuk yang membolehkan kita mengatakan bahwa perubahan itu dilakukan Navis. Terlihat ada pengaruh Kemarau terhadap ‘Datangnya dan Perginya’ edisi 1990. Perombakan itu dilakukan lama sesudah Kemarau dikarang dan terbit. Akibatnya, kualitas orangtua jadi sama dengan kualitas Duano. Keduanya sama berusaha untuk tidak berbuat dosa kepada orang lain, malah berusaha membantu orang lain. Dapat disimpulkan, dalam melakukan perombakan cerpen itu, Navis dipengaruhi oleh perkembangan cerita Kemarau. Kualitas Duano dipindahkannya jadi kualitas orangtua. Hanya saja, sifat itu hanya dilekatkan sebagai ciri orangtua—dikatakan tak pernah berbuat dosa lagi kepada manusia—yang tak dibuktikan dengan perbuatan. Halnya lain dengan Kemarau di mana memang terlihat Duano berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi kepada orang lain. Malah berusaha membantu mereka. la tak berusaha membalas kejahatan orang lain kepadanya. Dengan begitu, perombakan ‘Datangnya dan Perginya’ pada Robohnya Surau Kami edisi 1990 lebih dari perombakan bahasa. Ada sesuatu yang lebih esensial yang menyebabkan adanya perombakan itu.
Bagian yang diberi judul ‘bagian penutup’10 hanya bercerita tentang Arni yang menikah dengan anak Haji Tumbijo setelah cerai dari Masri. Masri yang menikah dengan teman sekerja. Duano yang kembali ke desa dan mengawini Gudam hingga Acin dan Amah resmi jadi anaknya. Kita tak tahu apa yang terjadi pada Masri, Irma dan anak yang dalam kandungan Arni ketika cerita berakhir. Bagaimana mereka melanjutkan kehidupan setelah orang pada tahu mereka terlahir dari perkawinan dua orang seayah. Kita hanya dapat menduga apa yang dapat terjadi pada mereka, mungkin pengalaman yang tak menyenangkan,11 yang tak selicin penutup Kemarau.12 Kita juga tidak tahu kelanjutan usaha Duano mentransformasikan kehidupan penduduk desa. Duano kelihatan cukup puas dengan mengawini Gudam, yang kelihatannya adalah pengalaman yang bertentangan dengan pengalamannya dengan istri-istrinya sebelumnya.
—————————
10Bagian-bagian Kemarau, kecuali bagian akhir, hanya dinomori, misalnya ‘bagian ketiga’. Bagian terakhir bukan hanya pendek, juga tak dinomori. Tapi diberi judul ‘bagian penutup’ yang menyarankan hakikatnya sebagai penutup cerita, yang dianggap perlu ada untuk menyelesaikan keruwetan penutup cerita sebelumnya. Tanpanya cerita dianggap tidak lengkap. Orang dapat menduga apa saja. Tentang Masri dan Arni yang hidup sengsara. Tentang kehidupan mereka yang dikacau Duano. Dan kemungkinan lain. Untuk menghindarkan ini, saya duga, Navis merasa perlu menambahkan ‘bagian penutup’, hal yang tak perlu dilakukannya bila novel itu ditulisnya pada masa yang sama dengan cerpen tadi. Akibat perbuatan masa, Navis marasa perlu ‘menambahkan sesuatu’. Ini sesuai dengan hakikat karyanya sebagai wacana budaya miliknya. Dan ini saya duga akan lebih jelas bila ia dapat dihubungkan dengan pembicaraan saya selanjutnya, terutama tentang alasan kenapa Duano sampai mengambil sikap yang berbeda dari orangtua pada cerpen sebelumnya, yang dapat dilihat dalam hubungan pertumbuhan diri Duano yang berbeda dari orangtua.
11Kaba Siti Syamsiah (Syamsudin St. Radjo Endah, 1961), yang juga bercerita tentang perkawinan sumbang, malah antara dua orang seibu-sebapa, memberikan penyelesaian yang menarik. Syamsiah dan Kaharuddin baru sadar mereka seibu-sebapa setelah sampai di kampung. Dengan nasihat perempuan tua yang menemani mereka dari Jakarta, mereka dapat menutup rahasia ini dari pengetahuan orang. Orang hanya tahu bahwa Kaharuddin membawa pulang adiknya, dan anak-anaknya, yang ditinggal mati suaminya—tugas biasa seorang ‘mamak’ (bdk. Junus, 1987:103). Dengan cara ini, ada jaminan anak-anak mereka tak akan diejek orang anak haram, hasil perkawinan dilarang agama, perkawinan antara muhrim. Kita tidak mengharapkan adanya komplikasi selanjutnya. Keadaannya lain pada Kemarau. Dapat diduga ada Orang yang tahu Masri dan Arni hasil perkawinan sumbang antara Masri dan Ami. Dan dapat pula diduga ada orang yang akan menggunakan informasi itu untuk mengejek anak-anak itu. Paling kurang untuk memandang rendah mereka. Karena itu, penyelesaian Kemarau bukan penyelesaian tuntas. Tapi mengundang persoalan selanjutnya, yang mungkin lebih ruwet.
12Ini dapat dibandingkan dengan penutup salah Pilih (Nur st. Iskandar, 1928). Asri meskipun kawin dengan Asnah yang sepersukuan dengannya, yang melawan kebiasaan adat, akhirnya diundang orang kampungnya untuk pulang kampung dan diangkat jadi kepala nagari. Bagi Asri dan Asnah sudah tidak ada lagi persoalan. Kesalahan mereka telah dimaafkan. Malah Asri kini diangkat jadi kepala nagari yang juga pimpinan adat kampungnya. Tapi karena Iskandar, saya duga, tidak mau meruwetkan persoalan, perkawinan Asri dan Asnah sengaja dibuatnya tak melahirkan anak. Seandainya ada anak, dapat diduga, anak itu akan jadi bahan ejekan orang kampung. Dan akan mengalami keruwetan karena berbako ke suku ibunya. Dengan alasan itu, sebagai pernah saya katakan (Junus, 1987:111), Iskandar sengaja tak membiarkan mereka beranak.
Kehidupan desa yang sebelumnya dapat dianggap bagian utama novel itu dilupakan.13 Tak ada berita/cerita tentang kehidupan desa selanjutnya. Penyelesaian yang ada hanya tentang kehidupan Duano dan anak-anaknya, tokoh cerita.
Dengan penutup itu, Navis telah menyempurnakan tugas keagamaan Duano yang telah dipersiapkan selama menetap di suatu desa14 di pinggir danau Maninjau. la contoh hidup garin modern yang Iain dari garin kolot ‘Robohnya Surau Kami’. Namun begitu, sebagai dikatakan tadi, kita tak tahu bagaimana kelanjutan tugasnya yang lebih besar, mentransformasikan kehidupan desa. la hanya berjaya menyempurnakan tugas pribadi. Apakah tak mungkin ia gagal melaksanakan tugas sosialnya. Atau Navis beranggapan demikian. Karena dianggap terlampau muluk untuk mengkriditkan Duano dengan tugas sosial itu, malah mungkin hanya suatu isapan jempol sebagai terlihat pada Panggilan Tanah Kelahiran Dt. Batuah Nurdin Yacub (1967) yang menceritakan keber hasilan Rusman membangun bendungan di kampungnya (Junus, 1982)—Navis sengaja tidak bicara tentang kelanjutan tugas sosial Duano.
———————————-
13Perkawinan Duano dengan Gudam menyebabkan Duano kini punya keluarga yang mestinya dihidupi. Dan tanggung jawab keluarga mungkin dapat menghalanginya melaksanakan tugas sosialnya. Rasa tanggung jawab keluarga menyebabkan ia akan mendahulukan kepentingan keluarga. Ini sesuai dengan ucapan Sutan Caniago dalam percakapannya dengan Duano. Saya kutipkan:
-
Bapak petani sebatangkara. Aku punya istri. Punya empat orang anak. Bebanku enam kali lebih berat dari Bapak. Kini Sutan Duanolah yang melongo.
-
Nasib kami petani di kampung ini tidak pernah berubah. Betapa giatnya kami bekerja, kami hanya mampu memberikan anak bini kami sehelai dalam setahun. Kami orang tani tidak pernah mampu membuatkan rumah untuk mereka. Bapak lihat pakaian ini. Hanya dari blacu. Inilah yang sanggup kubeli betapapun baiknya hasil panen. Lain halnya dengan jadi pedagang. Pedagang mempunyai kesempatan untuk berkembang. Setiap rumah yang bagus di kampung ini bukanlah punya petani, melainkan punya pedagang. (1967:10)
Berdasarkan kutipan ini, dapat kita duga tanggung jawab keluarga yang mesti dipikul Duano setelah mengawini Gudam, akan menyebabkan ia mulai mengurangi tanggung jawab sosialnya. la akan mengutamakan keluarga ketimbang kepentingan kampung. Dan selanjutnya dapat kita duga ini berarti berakhirnya usahanya memperbaiki kehidupan kampung yang mulanya begitu giat diusahakannya.
14Ini adalah Wacana budaya lain Navis yang terutama ditemui pada Kemarau yang dapat diberi berbagai interpretasi. Pelarian Duano ke desa pertama kali dapat dilihat sebagai pertapaan, lanjutan suatu tradisi. Atau ia dapat dilihat sebagai pemencilan diri dari kehidupan dan nilai kota yang menyengsarakan sesuai dengan kontradiksi yang streotip antara desa dan kota (Navis, 1967: 13). Duano melakukan dosa akibat kehidupan dan nilai kota. Dan cinta adalah segalanya adalah nilai kita yang diperkenalkan melalui wacana sastra —catatan 8. Ini yang bertanggung jawab terhadap dosa Duano. Menceraikan setiap isteri barunya tanpa peduli sedang hamil atau tidak. Memuaskan nafsu seks dengan pelacur—kehadirannya biasa dihubungkan dengan kehidupan kota—yang menyebabkan anaknya melarikan diri. Dan ini selanjutnya bertanggung jawab terhadap perkawinan sumbang Masri dan Arni. Dan untuk membebaskan diri dari dosa kota, Duano merasa perlu bertapa ke desa. Namun Navis tidak mutlak percaya kepada anggapan Streotip ini. Kehidupan desa baginya tidak ideal. Juga penuh dengan keburukan. Kehidupan agama yang kolot. Percaya kepada takdir dan doa dan mengharapkan pertolongan Tuhan tanpa berusaha. Percaya bahwa kemarau adalah takdir Tuhan yang perlu diselesaikan dengan doa. Atau mengharapkan bantuan pemerintah memberi mereka pompa untuk memompa air danau. Orang memilih menghabiskan waktu di kedai daripada mengangkut air dari danau yang tidak pernah kurang untuk mengairi sawah mereka. Hanya Duano yang memayahkan diri mengangkut air danau untuk mengairi sawahnya yang kering. Karena itu, sebelum dapat menjadi sumber kehidupan baru, kehidupan desa perlu diubah lebih dahulu. Semangat inilah yang menguasai Duano hingga merasa perlu mengunjungi Masri. Duano merasa ada sesuatu yang mesti dilakukannya di tempat Masri (1967:157). Dan ini menghalanginya berkompromi dengan Iyah. Dalam hubungan ini ia berusaha menjadikan desa sebagai pusat pendidikan baru untuk memperbaiki kehidupan manusia yang sudah bobrok—lyah membiarkan berlakunya suatu dosa. Dan ini dapat dilihat sebagai kehadiran wacana Pak Syafei pada Navis, yang pernah ditulisnya pada Siasat, 31 Oktober 1956. Saya kutipkan: ‘Menurut Pak Syafei, sebabnya di Kayutanam didirikan sekolah tersebut dan tidak di kota besar seperti Jakarta atau lainnya, ialah oleh karena Kayutanam itu suatu desa di tepi jalan besar dan terletak di tengah alam Minangkabau. Orang Minangkabau adalah orang perantau. Maka sifat-sifat yang demikian, sangat berguna untuk menyebarkan suatu sistem hidup sebagaimana yang dicita-citakan.’ Memang dapat dikesankan bahwa Navis menggunakan Kemarau untuk menyebarkan suatu sistem hidup, menyangkut etos kerja dan kegiatan agama. Pendeknya tentang sikap hidup yang saya anggap terjemahan paling tepat bagi ad Din ketimbang agama, yang saya bicarakan nanti. Dan ini ternyata tak menghalangi Navis berintegrasi dengan kehidupan budaya Indonesia yang berpusat di Jakarta. la punya andil yang menentukan kehidupan itu. Begitulah, pelarian Duano ke desa dapat dilihat sebagai suatu wacana budaya karena memerlukan pembicaraan tersendiri, ia tidak akan saya bicarakan lebih lanjut.
Navis hanya membawa kita ke dunia wacana. Garin modern hanya hadir sebagai wacana, lukisan ideal garin yang diinginkan Navis, antitesis garin yang dicaci dalam ‘Robohnya Surau Kami’. Dalam kebenciannya kepada garin yang biasa ditemui, Navis hanya ingin menyampaikan gagasan tentang seorang garin/ulama15 yang ideal.
Kemarau mau tak mau mesti berkembang ke arah penyelesaian ini karena Duano, sebagai telah dikatakan tadi, lain dari orangtua ‘Robohnya Surau Kami’, memang dipersiapkan untuk penutup ini.
——————————–
15Wacana Kemarau (133) ini:
“Mesti juga kukatakan rupanya pada guru? Apa guru kira, aku datang ke surau guru karena aku ingin mempelajari agama? Guru kira, perempuan lain itu datang karena pelajaran guru yang menarik hati? Aku, si Gudam, perempuan janda yang lain, perempuan-perempuan tua itu, sama saja. Kami datang hanya untuk perintang waktu. Guru lihat, mana perempuan yang bersuami yang serajin kami mehgikuti pelajaran di surau guru. Karena mereka punya kesibukan rumah tangganya. Aku, si Gudam dan perempuan janda itu datang karena kesepian. Tak enak jadi janda selama hidup guru. Aku akan gila kalau tak kawin. Akan gila. Akan gila,” katanya seraya terisak.
Ini adalah ucapan Saniah yang ditangkap basah Duano menanam pembenci di rumah Gudam supaya Gudam membenci Duano dan dengan demikian Duano akan bersedia mengawininya. Dari ucapan Saniah ini ternyata orang kampung bukan tertarik kepada ajaran (modern) Duano. Para perempuan itu mendengarkan ceramahnya hanya karena kesepian. Perempuan yang tidak kesepian, yang sibuk melayani suami, tak akan menghadiri ceramahnya. Ceramah itu hanya pengisi masa lapang mereka. Sama halnya dengan orang main layang-layang. Atau main domino di kedai kopi. Ini dilakukan orang sesudah menuai, sebelum turun lagi ke sawah. Malah ada yang lebih buruk. Mereka menghadiri ceramah Duano hanya karena ingin memikat Duano jadi suami. Ini menyebabkan kita mempertanyakan keefektifan ceramah Duano dan selanjutnya memungkinkan kita menyimpulkan ketakmampuannya mentransformasikan masyarakat itu sebagaimana dimimpikannya. Yang utama adalah hakikatnya sebagai wacana dan bukan kenyataannya di luar wacana.
Ia telah mengembangkan diri sebagai seorang penganut agama yang berusaha menjalankan perintah agama sesempurna mungkin. Menolong orang karena Allah tanpa mengharapkan keuntungan materi. Menolak riba. Tanpa menolak kuasa takdir16 dan doa Duano lebih menekankan perlunya manusia berusaha untuk menyempurnakan hidupnya. Daripada menghabiskan waktu untuk berzikir dan sembahyang minta hujan17 ia memilih mengangkut air dari danau untuk mengairi sawahnya.
——————————–
16Dalam hal ini pendapat Duano berbeda dari Rajo Bodi yang percaya kepada kuasa takdir. la menolak ajakan Duano gotong royong mengangkut air danau guna mengairi sawah mereka dengan memberikan helah berikut:
“untuk mengangkut air dari danau? Itu seperti pekerjaan tukang kebun saja. Tukang kebun yang mengangkut air untuk menyiram kebun bunga tuan besarnya. Buat apa kita payah-payah mengangkut air dari danau. Entah lusa, entah sebentar lagi, Tuhan menurunkan hujan. Sebagai petani, kita telah mengerjakan sawah kita. Kemudian kalau sawah itu kering karena hujan tak turun, Tuhanlah yang punya kuasa. Kita sebagai ummatNya, lebih baik berserah diri dan mempercayaiNya karena Ialah yang Rahman dan Ialah yang Rahim. Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Meskipun hujan diturunkanNya, hingga sawah-sawah berhasil baik, tapi kalau Tuhan menghendaki sebaliknya, didatangkanNya pianggang atau tikus, maka hasilnya takkan ada juga.” (1967:23)
Dan helah Rajo Bodi ini dijawab Duano dengan ucapan berikut:
“Kalau Tuhan punya mau, memang tak seorang pun yang kuasa menghalanginya. Itu adalah takdirNya. Tapi ada dua macam takdir. Takdir yang disampaikan dengan berpangku tangan dan tangan takdir yang diiringi dengan ikhtiar.”
17Sikap Duano mengenai hal ini dapat terlihat pada kutipan berikut:
“Lalu dikatakannya lagi, bahwa meskipun manusia itu ada yang mengingkari Tuhan, kafir, munafik, tapi kalau mereka itu giat berusaha, berani menantang kesulitan, mereka itu akan mendapat lebih banyak dari orang yang malas, meski orang yang malas itu rajin sembahyang. – Keimanan orang—katanya pula—bukan karena rajin bersembahyang saja. Tapi rajin mengikuti ajaran Nabi, namun untuk penghidupannya ia tetap juga bekerja keras. Mengapa kita yang tidak Nabi, yang tidak punya mukjizat, hanya mendoa-doa saja meminta kurnia Tuhan?” (1967:49)
Tuhan telah menyediakan air, sedanau, dan adalah tugas manusia kini untuk ‘mengalirkannya’ ke sawah mereka yang sayang tidak dilakukan. Karena sikap ini Duano lalu dianggap guru (agama) oleh orang kampung, ikutan mereka, meskipun mereka lebih sering menyeleweng dari ajarannya. Dengan sikap ini, ia tentu tidak mungkin mengambil sikap yang sama dengan orangtua ‘Datangnya dan Perginya’. la dengan keras menentang sikap Iyah. la kini malah siap dengan alasan ilmiah. Tentang kemungkinan keturunan orang yang kawin dengan saudaranya ditimpa cacat jasmani. Dan ia juga menolak saran Iyah untuk tak membiarkan mereka beranak, karena akan memperbesar dosa mereka (175)—tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk melahirkan zuriat. Duano kini bukan datang sebagai seorang ayah, tapi lebih utama, ia datang sebagai seorang mubaligh, yang mesti menyempurnakan, bukan hanya menyampaikan, ajaran Tuhan. Ini bertanggung jawab mengapa Kemarau berbeda dari ‘Datangnya dan Perginya ‘.
Perbandingan ‘Datangnya dan Perginya’ dan Kemarau memungkinkan kita mengatakan adanya transformasi pikiran pada Navis. Dan kita hanya dapat menduga faktor yang menyebabkannya. Dengan membatasi diri pada alasan sastra, ia mungkin dapat dilihat dalam hubungan perbedaan genre, cerpen dan novel. Ruang novel yang luas membolehkannya memberikan alasan terperinci. Memungkinkannya mengembangkan pribadi Duano. Sebaliknya dengan cerpen. Keterbatasan ruang menyebabkan semuanya mesti dan diringkaskan. Ada yang mesti diabaikan, Navis tidak punya peluang untuk mengembangkan ‘orangtua’. Ruang hanya mengizinkannya untuk menyatakan ciri orangtua tanpa dapat memperincinya. Dengan pendapat ini kita juga beranggapan Navis menggunakan cerpen untuk latihan menulis novel. Namun ia juga dapat dilihat dalam hubungan dengan faktor taksastra, perubahan wacana sosio-budaya, sebagai disarankan juga oleh judul buku Fairclough. Dalam masa delapan tahun, 1956—1964 telah terjadi perubahan wacana sosio-budaya dan ini memaksa Navis mentranformasikan pemikirannya. Akibatnya hadirnya wacana yang lain dari sebelumnya. Duano Kemarau lain dari orangtua ‘Datangnya dan Perginya’. la juga lain dari garin ‘Robohnya Surau Kami’ meskipun ia juga bermukim di surau.
Karena pembicaraan tadi ditumpukan kepada perbedaan antara Duano dan orangtua, pembicaraan selanjutnya akan menyorot kelainan antara Kemarau dan ‘Robohnya Surau Kami’. Kesan saya dalam membaca Kemarau ‘serentak’ dengan ‘Robohnya Surau Kami’ memungkinkan saya menduga bahwa Navis dalam mengarang Kemarau sengaja ingin menciptakan Duano yang sikap agama dan hidupnya adalah antitesis dari sikap agama dan hidup garin tua dalam ‘Robohnya Surau Kami’. Bila dalam membaca ‘Robohnya Surau Kami’ ada kesan garin tua itu ingin menghabiskan sisa umurnya sambil membuat ibadah melulu, sembahyang, zikir dan membaca Quran sampai mata jadi rabun, kita mendapat kesan Iain setelah membaca Kemarau. Dan ini dinyatakan Navis pada bagian awal novelnya. Saya kutip:
Tapi orang bertambah tercengang lagi, karena sisa umurnya dihabiskannya dengan bekerja keras. Padahal setiap orang yang mau mendiami sebuah surau adalah untuk menghabiskan sisa umur tuanya sambil berbuat ibadah melulu, sembahyang, zikir dan membaca Quran sampai mata jadi rabun. Memang itulah gunanya surau dibuat orang selama ini. (1967:3—4)
Begitulah, ada kelainan sikap hidup, terjemahan yang lebih tepat dari kata ‘agama’ untuk konsep ad-Din, antara Duano dan garin tua ‘Robohnya Surau Kami’. Pada garin agama hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, bagaimana manusia menyembah Tuhan, ibadat dalam arti sempit. Duano lain. la melaksanakan sikap hidup yang ajaran Islam, menyangkut seluruh kehidupan. Bagaimana menghidupi dunia karena sebelum sampai ke akhirat manusia mesti menghidupi dunia lebih dulu. Dunia jalan untuk ke akhirat. Untuk sampai ke akhirat orang perlu menghidupi dunia. Tanpa dunia tak ada akhirat untuk seseorang. Seorang ditentukan Tuhan masuk neraka atau sorga berdasarkan amal, perbuatannya, di dunia. Tuhan bukan menciptakan manusia hanya untuk akhirat. Manusia pertama kali diciptakan-Nya untuk menghidupi dunia. Dan sebagai khalifah Tuhan manusia mesti menemukan cara terbaik untuk menghidupi dunia. Melalui kehidupan dunia untuk sampai ke akhirat. Kesenangan hidup dunia akan membawa manusia kepada kesenangan hidup akhirat. Kemarau telah mengubah ‘agama’ pada ‘Robohnya Surau Kami’ menjadi ‘sikap hidup’ sebagai tercermin pada perbandingan kehidupan garin dan Duano.
Kita tak tahu Iatar belakang kehidupan garin pada ‘Robohnya Surau Kami’. Kita hanya tahu kehidupannya masa cerita berlaku. la garin yang menghabiskan sisa usia tuanya di surau sambil berbuat ibadah melulu, bukan amal yang berarti perbuatan. Sembahyang, zikir dan membaca Quran. Hidup dari sedekah orang. Dan dari fitrah orang setiap puasa. la tak merasa perlu berusaha karena ini akan mengurangi masanya untuk beribadah, tentunya tanpa beramal. Duano lain. Akhirnya kita tahu latar belakangnya.
Kita tahu dosa yang pernah dilakukannya membawanya ke desa di tepi danau. Kita tahu peran Tumbijo—hanya dapat diduga karena tak diberitahu apa yang ‘dibisikkan’-nya kepada Duano18—mentransformasikan Duano19 keluar dari pemencilan, berintegrasi dengan kehidupan desa. Dengan ikhlas, tanpa pamrih, hanya karena Allah, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Bukan hidup dari sedekah, tapi berusaha untuk kehidupannya, padahal ia hanya seorang diri. Begitu kuatnya usahanya hingga punya simpanan uang untuk membantu orang lain. Dan kesibukan kerja tak menghalanginya menghidupkan surau. Masih punya waktu untuk memberikan ceramah agama, meskipun khalayaknya hanya para perempuan yang kesepian, yang hadir bukan karena tertarik kepada ceramahnya, tapi untuk menghabiskan waktu dan untuk memikatnya.
—————————–
18Kita hanya mungkin menduga mengapa Navis merahasiakan apa yang dikatakan Tumbijo kepada Duano. Pertama, ia menganggap, dari jalan cerita, pembaca toh akan dapat memikirkan apa yang dikatakan Tumbijo kepada Duano. Jadi tidak ada gunanya dieksplisitkan. Malah ditakutkan, pengeksplisitan akan menyebabkan ia terasa sebagai dakwah verbal yang membosankan pembaca. Di samping itu, ada kerugian lain dengan pengeksplisitan. la akan mengikat perjalanan cerita. Orang dapat mempertanyakan novelnya bila jalan cerita menyimpang dari apa yang pernah dieksplisitkannya. Dan adalah lebih baik untuk tak mengeksplisitkannya. Membiarkan pembaca merumuskannya sendiri. Dan ini memang diharapkan Navis dari pembacanya. la tidak mengharapkan pembaca yang pasif dan tak berpikir.
19Tumbijo punya peran penting dalam hidup Duano. Keinginannya memenuhi panggilan Masri karena ada peran Tumbijo. Masri mendapatkan alamatnya dan menyuratinya setelah bertemu dengan Tumbijo yang tinggal di Makasar, dan pertemuan itu dianggapnya bukan suatu kebetulan (1967:115—6). Malah kemudian, Arni setelah bercerai dengan Masri, kawin dengan anak Tumbijo.
Ini melengkapkan kontras Kemarau dan ‘Robohnya Surau Kami’. Garin tua ‘Robohnya Surau Kami’ yang dikutuk. Begitu terkutuknya hingga bunuh diri yang menurut Islam dosa besar. Kita tak tahu, ia tahu agama atau tidak karena kita tak diberitahu apakah ia pernah mempelajari agama. la jadi garin hanya karena menghuni surau. Halnya Iain dengan penghuni surau Kemarau. Meskipun menghuni surau namun ia tak pernah disebut garin. Mungkin karena cara hidupnya lain dari cara hidup garin yang biasa dikenal orang. la bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga lebih kaya dari penduduk kampung. Berbeda dari garin yang biasa dikenal orang, ia tidak hidup dari sedekah. la malah berjuang melawan arus (1967:121).
Dengan perbandingan terakhir ini saya tutup pembicaraan saya tentang persamaan dan perbedaan antara Kemarau dengan ‘Datangnya dan Perginya’ dan ‘Robohnya Surau Kami’, tanpa perlu meringkaskannya lagi.
000
Leave A Comment