A.A. NAVIS
Pengantar Sebuah Otobiografi
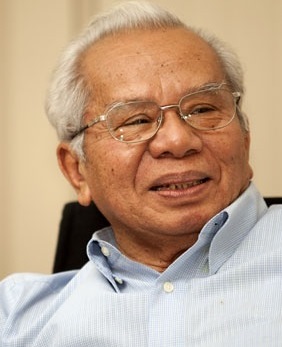 SIAPAKAH Ali Akbar Navis? Pertanyaan yang aneh juga. Tetapi barangkali juga bukan. Dalam nada senda gurau ada yang menyebutnya “pencemooh kelas wahid” atau, dengan istilah yang lebih canggih, “intelektual par excellence”. Bukankah salah satu ciri keintelektualan adalah kecenderungan untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu? Intelektual bisa mempertanyakan hal-hal yang biasanya tak ditanyakan dan tak tertanyakan orang lain. Ia mempersoalkan semua, malah juga hal yang semestinya bisa diterima begitu saja. Jadi julukan yang demikian terhadap Navis mungkin tepat juga. Ia memang selalu mempertanyakan apa saja. Tetapi inilah soalnya. Ia tidak sekadar mempertanyakan, mengecam, mencela, atau kadang-kadang, memuji. Ia berbuat. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan. Ia bisa menjadi pelopor, pendukung, penggerak, atau pengecam dan, tak pula jarang, penentang dari gagasan pembaruan atau perubahan, tetapi sebagai penonton yang pasif ia tak hendak. Berlagak sebagai mandor yang sibuk melihat para kuli bekerja mengangkat batu dan semen dalam proses perubahan sosial, ia pun enggan. Maka, bagaimanakah ia harus dilukiskan? Barangkali untuk mudahnya, katakan saja ia adalah salah seorang “daerah”, yang paling mempunyai “nama nasional”. Dalam konteks yang serba sentralistis yang kini menjangkiti sendi-sendi kehidupan kenegaraan dan kebangsaan kita, mempunyai “nama” di pusat ini tentu bisa dianggap suatu prestasi juga. Apalagi ia tidak berada dalam jalur birokrasi, yang mempunyai seperangkat peralatan untuk “memusatkan” apa saja atau siapa saja.
SIAPAKAH Ali Akbar Navis? Pertanyaan yang aneh juga. Tetapi barangkali juga bukan. Dalam nada senda gurau ada yang menyebutnya “pencemooh kelas wahid” atau, dengan istilah yang lebih canggih, “intelektual par excellence”. Bukankah salah satu ciri keintelektualan adalah kecenderungan untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu? Intelektual bisa mempertanyakan hal-hal yang biasanya tak ditanyakan dan tak tertanyakan orang lain. Ia mempersoalkan semua, malah juga hal yang semestinya bisa diterima begitu saja. Jadi julukan yang demikian terhadap Navis mungkin tepat juga. Ia memang selalu mempertanyakan apa saja. Tetapi inilah soalnya. Ia tidak sekadar mempertanyakan, mengecam, mencela, atau kadang-kadang, memuji. Ia berbuat. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan. Ia bisa menjadi pelopor, pendukung, penggerak, atau pengecam dan, tak pula jarang, penentang dari gagasan pembaruan atau perubahan, tetapi sebagai penonton yang pasif ia tak hendak. Berlagak sebagai mandor yang sibuk melihat para kuli bekerja mengangkat batu dan semen dalam proses perubahan sosial, ia pun enggan. Maka, bagaimanakah ia harus dilukiskan? Barangkali untuk mudahnya, katakan saja ia adalah salah seorang “daerah”, yang paling mempunyai “nama nasional”. Dalam konteks yang serba sentralistis yang kini menjangkiti sendi-sendi kehidupan kenegaraan dan kebangsaan kita, mempunyai “nama” di pusat ini tentu bisa dianggap suatu prestasi juga. Apalagi ia tidak berada dalam jalur birokrasi, yang mempunyai seperangkat peralatan untuk “memusatkan” apa saja atau siapa saja.
Banyak yang mengenalnya hanya sebagai pengarang “Robohnya Surau Kami”, sebuah cerita pendek yang ditulisnya di saat sentralisasi dalam hampir segala bidang, masih berada entah di mana. Memang benar, cerita pendek ini, kalau bukan salah satu karya sastra terbaik yang pernah dihasilkan di Indonesia, setidaknya adalah yang paling terkenal. Jadi identifikasi Navis dengan karyanya masuk akal saja. Namun Navis lebih, malah teramat lebih, dari sekadar penulis cerita pendek ini, betapapun ia tak pernah berhasil menyembunyikan kebanggaan atas karyanya yang gemilangnya ini. Kalau begitu, sebagai apa ia sebaiknya dikatakan? Pertanyaan ini bukan mengada-ada. Coba saja perhatikan jalan hidupnya. Tak usahlah diperhatikan ruang lingkup perhatian serta penjelajahan pemikirannya. Karena dalam ini ia telah jauh mengatasi segala kendala yang mengitarinya ataupun yang terlekat pada dirinya. Simak sajalah corak aktivitas yang pernah dijalaninya. Dalam dunia kesenian ia pernah tampil sebagai pemusik, pemahat, penulis, dan malah juga impresario, meskipun hanya tahap lokal dan tak pula punya modal. Barangkali tak pula salah kalau dikatakan bahwa baginya kesenian, meskipun penting, hanyalah sebagian dari aktivitas yang lebih luas dan beragam dalam bidang kebudayaan. Dalam wilayah kegiatan ini ia kerap muncul dalam berbagai seminar, sebagai pemakalah atau pembahas, atau menulis dan mengedit buku tentang kebudayaan dan sejarah daerahnya. Sebagai seorang aktivis dan pemikir kebudayaan, ia bisa tampil sebagai politikus, yang tentu saja, harus berpihak pada aturan main yang telah digariskan oleh sistem kekuasaan. Namun dalam keharusan pada keberpihakan politik ini ia tak pula hentinya untuk meneguhkan kehadiran dirinya sebagai pribadi, bukan sekadar angka dalam pemungutan suara. Sebagai birokrat ia “memecat” atasannya-ia berhenti menjadi pegawai negeri. Ia pun pernah pula menjadi pemimpin redaksi sebuah surat kabar “resmi”. Sedemikian gairahnya ia ingin memberitakan segala sesuatu yang pantas diberitakan, sehingga ia pun alpa atau, bisa juga, melupakan, tanggung jawab dari keresmian berpihak yang harus dipikulnya. Maka ia pun kembali sebagai suami dan ayah, yang harus mencari kesibukan lain. Tetapi ia pun seorang pendidik, yang mungkin hanya berpihak pada suatu corak masa depan bangsa. Dan, tak kurang pentingnya, ia pun terlibat juga, bahkan salah seorang pemrakarsa, dari usaha pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan, seperti usahanya mengembangkan lembaga keuangan desa dan kemudian, aktivitasnya dalam Gebu Minang.
Maka, barangkali saya bisa dimaafkan, kalau kini angan saya, entah mengapa, melayang pada Almarhum Sutan Takdir Alisyahbana. Dengan keharuan yang mendalam saya terkenang pada sang pencetus Polemik Kebudayaan, yang baru beberapa bulan yang lalu meninggalkan kita. Ia, STA, sang novelis yang filosof ini, mengidamkan lahir dan tumbuhnya suatu corak kebudayaan (sebagai konfigurasi dari berbagai nilai fundamental, seperti artistik, ekonomis, keilmuan, dan sebagainya) Indonesia baru, yang rasional, progresif, dan kompetitif. Dengan bermain kiratabasa ia mengimpikan mekarnya corak kehidupan kebudayaan yang dapat merangkul inti hakikat dari asal kata “budaya”, yaitu ‘budi” dan “daya”. Dan ia pun membayangkan tumbuhnya tradisi “manusia Renaisance” di kalangan bangsanya. Meskipun kedengarannya idealistis, malah juga utopis, tetapi ia, Takdir, tak bersikap ahistoris dalam gambarannya tentang manusia ideal ini. la tidak bermaksud memindahkan situasi historis Eropa di saat akan memasuki zaman modern ke bumi Nusantara. la hanya ingin menjadikan sebagai model bagi Indonesia masa depan suatu sosok manusia ideal yang pernah menjadi ciri khas dari suasana kultural dari zaman ketika “individu ditemukan kembali” (sebagaimana Jacob Burkhardt menyebut “zaman Renaisance”) itu, yaitu uomo universale. Di saat kecenderungan teknokratis telah semakin menjadi-jadi dan di kala spesialisasi dalam keahlian telah semakin cenderung secara konseptual meniadakan saling keterikatan alam dan kenyataan kehidupan, Takdir menginginkan kembalinya peran manusia yang dapat merangkai berbagai spesialisasi dalam kesadaran yang humanistis. Di saat pluralisme dalam kehidupan sosial telah semakin keras dan persaingan negara-negara nasional semakin mengental, ia mengidamkan kembalinya peranan tokoh yang universalistis, yang dapat membendung segala corak perilaku dan pemikiran yang parokial.
Manusia ideal akan tetap ideal. Sekali yang ideal itu telah terwujud, ia pun berhenti sebagai sesuatu yang diidealkan. Dan Navis adalah tokoh yang riil berbuat. Hanya saja keluasan wilayah aktivitasnya dan keengganannya untuk membatasi perhatian kepada apa yang dianggap orang “keahlian”-nya memperlihatkan bahwa desakan “universalisme” dalam kegiatan sosial-politik dan kultural bukanlah suatu “utopia” belaka. Setidaknya demikianlah halnya kalau saja semua hal itu dilihat dari perspektif Navis, sang aktivis. Namun masalah sosial-kultural dari kehadiran perilaku dan perhatian yang “universal”, serba menyeluruh akan muncul kalau perspektif tersebut dialihkan pada masyarakat dan waktu yang menjadi wadah dari aktivitas. Kalau telah begini maka tampaklah bahwa peristiwa kimia-sosial tak selamanya ramah dalam menerima kecenderungan yang “universalistis”. Maka jadilah Navis, seperti juga para “universalis” lain, seorang yang kontroversial-ada yang setuju, ada yang pura-pura tak perduli, dan tak pula kurangnya yang menolak. Ia mungkin diterima tetapi dapat pula disingkirkan. Tetapi dalam suasana apa pun “kehadiran”-nya seakan selalu dirasakan. Pada “kehadiran” yang seakan menetap inilah salah satu keunikan dari tempat dan peran Navis di daerah kelahirannya bisa ditemukan.
Mungkin “kehadiran” yang dirasakan ini disebabkan Navis mempunyai kemampuan untuk menggantikan dirinya dengan teks-teks yang dihasilkannya. Apa pun yang ingin diprakarsainya dan apa pun yang ingin atau telah dilakukannya, ia selalu menjadikan teks sebagai saluran utama untuk menggapai masyarakat yang jadi sasaran normatifnya. la memang seorang penulis. Dengan teks yang dihasilkannya ia dapat mengingkari tirani jarak dan waktu yang menghambat hubungan langsung antara dirinya dengan sasaran yang ingin dicapainya. Dengan teks ia menjadikan dirinya selalu “hadir”. Ia bisa berberita, berpetuah, atau bertengkar, Dengan berbagai peralatan literer ia pun dapat mengatakan sesuatu secara simbolik, seakan-akan semuanya hanyalah rekaan yang terjadi “di sini”, tetapi harus dianggap sebagai peristiwa yang terjadi di negeri antah-berantah. Ia mungkin mengatakan yang sebenarnya, tetapi dikesankannya sebagai yang hanya “benar” dalam imajinasi. Atau, bisa saja yang dikatakannya itu adalah “sebenarnya” tak lebih dari hasil rekaan belaka. Semuanya bisa dilakukannya liwat teks.
Kalau telah begini, mestikah diherankan jika otobiografinya mengasyikkan? Kini, liwat teks, ia ingin menampilkan dirinya. la hendak menceritakan yang sebenarnya sebagai “yang sebenarnya”. Otobiografi Navis tak hanya memaparkan berbagai kisah kehidupannya, yang kadang-kadang lucu, tak jarang pula mengharukan atau malah menyebalkan dan sebagainya, tetapi, lebih daripada itu, kisah kehidupannya ini berisikan untaian dari berbagai dialog yang pernah terjadi antara dirinya dengan masyarakat dan zamannya. Dengan kata lain ia juga berkisah tentang berbagai pola peristiwa kimia-sosial yang dilaluinya di daerah kelahirannya, di Sumatera Barat.
Dalam hal yang terakkhir inilah otobiografi, yang disusun secara konvensional dengan berkisah mengikuti alurwaktu, memperlihatkan tiga periode kehidupan Navis. Kalau pada periode pertama, ia, seperti kita semua, hanyalah tenggelam dalam “dunia yang bukan ciptaannya” (ungkapan ini adalah “plagiat” saya dari sebuah judul novel Amerika, yang sekian tahun yang lalu sangat disenangi Motinggo Busye), maka pada periode kedua ia telah semakin tegas dalam menyatakan sikap. Meskipun, pada periode pertama, ia bisa juga bercerita tentang kota kelahirannya, dengan cukup mengasyikkan dan juga dengan rasa bangga, tetapi dalam bercerita ia telah menggabungkan kenangan dengan pengetahuan yang didapatkan dari orang Iain. Pada periode kedua, yang tampil adalah Navis yang telah terlibat dalam berbagai peristiwa kimia-sosial. Tetapi ia barulah di pinggiran. Dan, barangkali tidaklah berlebihan kalau dikatakan “Robohnya Surau Kami” merupakan salah satu tonggak yang menentukan dalam roda kehidupannya selanjutnya. Peralihan roda kehidupan ini tampil dengan jelas pada periode ketiga, ketika Sumatera Barat harus beranjak dari suasana krisis yang paling traumatis di abad ini. Mungkin terasa berlebihan, tetapi tidaklah terlalu salah kalau dikatakan bahwa pergolakan sosial-politik serta dinamika sosial-kultural Sumatera Barat sejak awal 1960-an dan terutama sejak lahirnya Orde Baru bisa dilihat melalui prisma biografi Navis. Dalam periode inilah “kehadiran”-nya dalam berbagai corak dan ragam peran selalu “ada”. Diterima atau ditentang ia “ada”. Janganlah pula kaget, kalau nanti ternyata aspek-aspek tertentu dari periode ini bisa mengundang perdebatan yang keras.
Otobiografi ditulis untuk kita, sang pembaca. Karena itu otobiografi tidaklah sekadar berkabar tentang masa Ialu, tetapi juga sebuah ajakan untuk berdialog. Dengan sifatnya yang pribadi dan subjektif, maka kemampuan dialog yang dipunyai otobiografi bisa lebih intens daripada yang diajukan oleh biografi atau sejarah, sekalipun. Yang satu ingin berkisah tentang seseorang sedangkan yang Iain tentang masyarakat, namun kedua genre tentang masa Ialu ini berusaha sejauh mungkin untuk menekan aspek kewacanaan, yang dialogis. Keharusan tidak-berpihak, sebagaimana yang diajarkan oleh sebuah mitos-akademis yang tak mudah mati, yang bernama objektivitas, bukanlah patokan yang terlalu mudah untuk diingkari. Memoir, tetangga otobiografi yang terdekat, sekalipun tak bisa mengatasi kekentalan dialog yang diberikan otobiografi. Jika memoir hanya ingin mengatakan apa-apa yang dianggap penting yang bisa teringat, maka otobiografi adalah usaha pemaparan seluruh kehidupan.
Setiap otobiografi-yang ditulis langsung ataupun yang dituliskan orang Iain-pada dasarnya adalah sebuah kesaksian pribadi tentang perjalanan kehidupan yang telah dilalui, tentang kegairahan dan kegelisahan, kesenangan dan kebanggaan, kedukaan yang pernah menimpa, atau apa saja. Tetapi tak pula jarang otobiografi adalah pula suatu pertanggungjawaban, yang tidak sekadar berupa penghamparan ingatan tentang masa Ialu yang telah dilalui. Kita pun berhadapan dengan perenungan yang reflektif. Mengapa hal itu dilakukan, bagaimana kalau sekiranya tidak demikian? Rasionalisasi dan usaha pembenaran tak terhindarkan. Apologi atau, malah mungkin, penyesalan bisa pula ditemukan. Karena itu bisa saja sebuah otobiografi tampil sebagai pengelanaan alam pikiran, jauh melampaui pengalaman empiris si pengisah.
Bagaimanapun kecenderungan internal sebuah otobiografi, kehadiran wujudnya adalah hasil dari dua tahap seleksi. Yang disampaikan adalah, pertama, yang terekam dalam ingatan atau catatan, dan kedua, yang ingin dikisahkan. Tak semua hal bisa teringat atau terekam dan tak pula semua yang teringat atau terekam itu dianggap pantas untuk dikisahkan. Seleksi yang kedua ini adalah sesuatu yang lumrah, karena otobiografi adalah sebuah teks yang memungkinkan kedirian seseorang, mungkin yang paling hakiki, ditampilkan dalam kancah wilayah-publik. Kalau demikian, manakah yang lebih penting hal yang lulus seleksi daripada yang digugurkan dalam seleksi?
Pertanyaan ini sah, tetapi tak terlalu relevan. Sebab hasil akhir dari kedua corak seleksi tersebut adalah awal dari dialog yang dipantulkan oleh otobiografi. Jadi meskipun tak terbebas dari tanggung jawab akan keharusan adanya kejujuran-yang dikisahkan itu adalah yang benar dialami, sebagaimana yang sejujurnya teringat atau terekam-otobiografi, seperti genre kreatif lainnya, merupakan pantulan dari suatu kebebasan. Kalau begitu, pertanyaan lain dapat diajukan. Bagaimanakah hubungan otobiografi dengan karya kreatif yang ditampilkan sebagai suatu rekaan? Pertanyaan ini semakin penting kalau dihadapkan pada Navis. la adalah penulis karya kreatif yang mempunyai nama. Bilakah karya rekaannya sesungguhnya fiktif dan bila pulalah rekaan tersebut adalah stilisasi kreatif dari pengalamannya? Sejauh manakah terbebas corak pengisahan otobiografinya —susunan naratif, penekanan signifikan kenangan yang dikisahkan, rekonstruksi dialog, dan sebagainya—dari pengaruh gaya rekaannya yang fiktif? Bukankah bentuk pengisahan adalah salah satu corak dari dialog?
Otobiografi Navis, seperti juga kesaksiannya tentang mengapa ia mengarang yang pernah diterbitkan, bisa berkisah tentang proses penciptaannya. Cerita pendek ini atau itu, katanya, ditulis setelah ia melihat ini atau mengalami itu. Novel ini ditulis karena hal ini, dan sebagainya. Tetapi hampir semua yang ditulisnya itu tidaklah sekadar “perentang-perentang hari menjelang petang”, sebagaimana seorang yang tengah berpuasa mengatakannya. Meskipun memakai gaya senda gurau, ia tak bermaksud agar tulisannya hanyalah dipakai sebagai pembunuh waktu, sambil “menunggu beduk belum ditabuh”. Dalam berkisah, secara tersamar atau terang-terangan, ia ingin mengatakan sesuatu yang melebihi dari cerita yang dikabarkannya. Sesuatu itu bisa saja suatu pandangan yang keras dan disampaikan dalam nada yang mencekam. Kadang-kadang itu hanyalah hal enteng yang mungkin terlupakan. Tak jarang pula yang disampaikannya cukup menggetarkan.
Langsung ataupun tak langsung, gamblang atau tersamar, Navis, dengan kisah-kisah rekaannya, memasuki berbagai masalah sosial, politik, dan kebudayaan. Hampir kesemuanya memperlihatkan hasil dialog internal yang intens yang dilakukannya dengan apa yang dilihat dan dialaminya. Karena itulah ia menyatakan sikap terhadap kesemuanya. Karena itulah kadang-kadang ia bisa meradang pada kritikus sastra, atau bisa juga pada kita, sang pembaca, karena dianggapnya gagal dalam menangkap apa yang sesungguhnya yang ingin dikatakannya. Mungkin ia lupa bahwa teks yang dihasilkannya sekaligus meniadakan hubungannya yang langsung dengan pembaca. Teks yang jadi jembatannya dengan pembaca, sebenarnya adalah pula pembatas hubungan yang langsung. Dalam kejengkelan ini bisa jadi ia tak perduli bahwa teks yang dihasilkannya itu tak ubahnya dengan sebuah anak panah yang telah terlepas dari busurnya. Sekali terlepas, anak panah terbebas dari kekuasan mutlak sang pemanah. Apa pun alasannya, Navis memang mencoba juga melalui otobiografinya atau berbagai eseinya untuk membujuk kita agar mengikuti interpretasinya tentang teks yang telah dihasilkannya itu.
Bisa jadi ia akan pernah berhasil sepenuhnya dalam hal pembujukan ini. Tetapi andaipun ia gagal, maka ini adalah pertanda betapa teks-teksnya, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, telah mencapai sasaran yang berbeda-beda. Teks-teks literer dan simboliknya itu telah berhasil memancing berbagai corak rangsangan perasaan dan pemikiran.
Sebagai kesaksian dan renungan terhadap liku-liku kehidupannya dan proses kimia-sosial yang dialaminya dalam berbagai kegiatan, otobiografi memantulkan dengan keras sikap batin dan pemikirannya tentang berbagai masalah kemasyarakatan. Maka dalam otobiografinya tampaklah figur Navis sebagai seorang yang realistis, meskipun enggan melepaskan idealismenya. Betapapun ia menyadari akan kuatnya hegemoni sistem hirarki, Navis tak secuil pun ingin meninggalkan hasrat egaliter—suatu hasrat yang dirasakannya tidak saja sebagai bagian dari bawaan pribadi, tetapi juga keharusan kultural. Kendatipun sepenuhnya sadar dan mengetahui fungsi kesakralan agama yang harus dipikul para ulama, ia tak pernah pula lupa mengingatkan realitas sosial yang tak bisa dianggap tak ada. Maka begitulah, kelihatan pula ia harus menjalankan berbagai kompromi politik dan sosial, namun tetap berusaha menjaga landasan sikap kultural dan idealisme awal yang telah dipatrikannya. Kalau disederhanakan dan teramat disederhanakan, maka yang tampil ialah pemikiran yang menginginkan berlanjutnya egalitarisme Minangkabau, demokrasi modern, keadilan sosial dan ekonomis, serta rasionalisme dalam tradisi dan agama. Akhirnya yang tampak adalah hasrat akan kebebasan dalam penciptaan dan pendapat serta keengganan terhadap segala corak sentralistis, yang bagaimanapun selalu memarjinalkan peran, daerah, atau pandangan yang berbeda.
Kemungkinan perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap karya-karya kreatif, yang rekaan, dari Navis tetap terbuka, Namun pada umumnya dapat dikatakan bahwakarya kreatif itu memantulkan hal-hal tersebut di atas dengan cukup keras. Malah wilayah karya kreatif ini memberinya kebebasan yang cukup luas. Meskipun ia, sebagaimana pengarang lainnya, tak sepenuhnya terbebas dari konvensi literer dan bahasa, yang telah memberinya saluran bagi ekspresi diri, tetapi sekaligus memberinya batas-batas agar bisa komunikatif, ia dapat memasuki lekuk-lekuk yang terdalam dari tokoh-tokoh rekaannya. Dalam karya imajiner ia, kalau mau, bisa menyembunyikan dirinya, dengan berlagak hanya sebagai pencatat, tetapi sekaligus membongkar segala hal yang tersembunyi dari wilayah-publik yang dipunyai tokoh kisahnya. Dengan kebebasan ini Navis dengan melenggang lenggok memasuki hampir seluruh wilayah permasalahan kemasyakaratan dan politik, bahkan juga yang bercorak psikologis. Berbagai tulisan yang dimuat dalam buku ini memperlihatkan betapa kaya kemungkinan pemikiran yang bisa ditampilkan oleh penjelajahan Navis yang relatif bebas ini.
Dengan perbandingan ini, terasalah betapa terkekangnya kebebasan yang dimiliki sebuah otobiografi. Betapa banyak wilayah tabu yang tak boleh dimasuki oleh sebuah otobiografi. Tak ada kebebasan otobiografi untuk memasuki dunia perasaan dan pikiran orang Iain, meskipun secara intelektual dan intuitif si penulis mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Otobiografi hanya bisa atau, lebih tepat, dibolehkan oleh kesopanan moral, untuk menangkap kesan dari pola perilaku orang Iain. Hanyalah wajah-publik seseorang yang secara moral bisa direkam dan di-tebak. Sedangkan yang berada di belakang wajah-publik, yaitu kedirian yang otentik, berada di luar jangkauan otobiografi. Keterbatasan ini terpantul juga dalam otobiografi Navis, sang satiris, meskipun ia kadang-kadang ingin juga meniadakan batas-batas yang dipaksakan itu.
Begitulah, otobiografi Navis memang memperkenalkan kita pada tahap-tahap kehidupan, jalur dan liku pengalaman hidup yang dilaluinya dan berbagai corak kimia-sosial yang dijalaninya serta pergolakan batin yang pernah dialaminya. la tampil sebagai pribadi yang tanpa henti menghadapkan dirinya pada berbagai masalah yang dihadapi komunitas daerah dan masyarakat bangsa. Tetapi otobiografi menghalanginya untuk merumuskan pandangannya tentang manusia sebagai pribadi yang utuh pada diri masing-masing. Dengan kata Iain, otobiografi bukanlah saluran untuk mendapatkan Navis tentang manusia yang riil, bukan yang hipotetis ataupun hasil abstraksi filosofis. Otobiografi adalah perkenalan yang belum lengkap dengan Navis. Esei yang ditulisnya, makalah yang aiajukannya dalam seminar, malah juga buku yang diterbitkannya, hanya memperkenalkan pada kita pengetahuannya dan pandangannya tentang berbagai aspek kebudayaan dan kemasyarakatan, tetapi bukan tentang manusia. Kekurangan ini lebih mungkin diisi oleh karya kreatif Navis. Liwat saluran inilah Navis muncul sebagai pembedah manusia-manusia yang riil, termasuk dirinya. Secara langsung ataupun tidak Iiwat karya kreatif, yang rekaan ini, ia tak jarang mempertanggungjawabkan kehadiran sebagai pribadi, bukan sekadar sebagai seorang pemangku sebuah peran sosial atau politik.
Siapakah Ali Akbar Navis sesungguhnya? Maka, jawab akhir saya barangkali hanya, “Biarlah teks yang polisemi melemparkan rangsangannya yang berbeda-beda”. Tetapi bukankah ini sama saja dengan tak jawaban. Kalau begitu, jawaban anti-klimaks tak terhindarkan. la adalah seorang sastrawan dan seorang haji yang kini merayakan ulang tahun ke-70. la seorang ayah yang dengan senyum bisa melihat semua anaknya kini telah “jadi orang”. Semuanya adalah hasil pendidikannya bersama sang isteri, yang meskipun hanya sebentar berpacaran, tetapi sampai kini telah memberikan padanya suasana yang bisa disebutnya dengan rasa haru “home, sweet home”. Dan jika kebetulan kita bertamu ke rumahnya dan menanyakan pada isterinya di manakah Navis gerangan, janganlah heran kalau sang isteri memberi jawaban seperti meniru isteri Ajo Sidi, si pengacau batin dari ‘Robohnya Surau Kami’, “Kerja, dia pergi kerja”. Jangan-jangan Navis adalah “Ajo Sidi”.
***
Leave A Comment